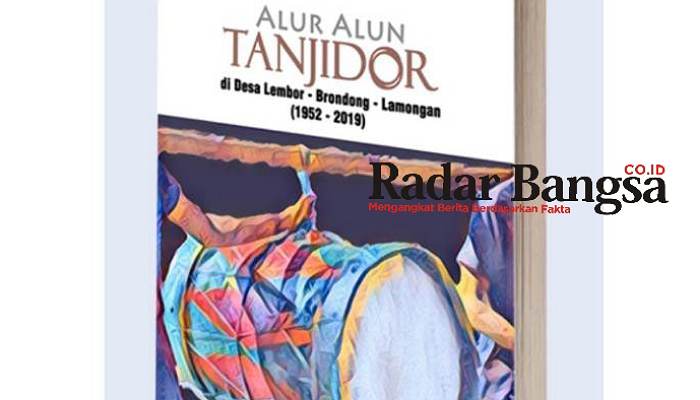LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Bisa dibayangkan bahwa kesenian (baca juga: kebudayaan) mempunyai sifat seumpama air atau bisa juga disebut seperti angin. Cair sekaligus lembut. Sebab itulah kesenian memiliki kemampuan alami untuk merasuk, menembus batas-batas wilayah negara, suku, adat istiadat sub-kultur, keyakinan bahkan agama.
Tidak hanya berhenti disitu, kesenian juga mampu memberi pandangan baru pada arti hidup, menggerakan geliat pemikiran, memberikan rasa senang dan tentram, serta lebih jauh lagi, kesenian menjadi unsur penting dalam usaha membangkitkan atau memperindah sebuah peradaban.
Lewat buku ini, kesenian yang memiliki sifat dan peran seperti di atas, kesenian Tanjidor tentu saja bisa disebut termasuk salah satunya.
Dalam anggapan banyak orang, tanjidor lebih lekat dan identik dengan kebudayaan masyarakat Betawi-Jakarta, tetapi jika dikaji lebih jauh, tanjidor ternyata telah menyebar di sepanjang wilayah pesisir utara laut Jawa hingga sampai di Desa Lembor-Brondong-Lamongan ini.
Perjalanan Tanjidor ini tentu saja memiliki kisah perjalanannya sendiri, tidak hanya soal penyesuaian dengan kultur masyarakat masing-masing yang menerimanya tapi juga bisa dibilang masih diliputi misteri dan hal-hak yang bersifat magis. Hal itu menyangkut banyak hal, baik mengensi asal muasal bangsa yang pertamakali mengalunkannya, manfaat dan kegunaan, cerita pahit dan manis, proses pertunjukan, ragam alat-alat musik serta keunikan lain di dalamnya.
Sebelum kita mengenal Tanjidor sebagai kesenian tradisi rakyat yang humanis, tanjidor ini juga mengandung petuah hidup sekaligus hiburan bahkan difungsikan sebagai media dakwah sebagaimana halnya hari ini.
Barangkali tidak banyak yang menduga bahwa, tanjidor merupakan kesenian musik yang dibawa masuk ke Nusantara oleh pemerintah Kolonial Belanda. Dimana saat itu, kesenian tanjidor ini dimainkan oleh budak-budak pribumi yang mereka latih. Yang sangat mungkin dalam prosesnya terdapat unsur pemaksaan dengan kekerasan kepada para budak pribumi itu.
Pada setiap pertunjukannya, para budak memainkan musik sedangkan para pejabat teras pemerintah kolonial mendengarkan sambil berdansa Polka, sekaligus menikmati kekayaan sumber daya alam Nusantara. Meski Tanjidor dibawa oleh Pemerintah kolonial belanda, bukan berarti merekalah penemunya, mereka menerimanya dari bangsa lain.
Mengenai asal muasal kesenian ini beberapa Antropolog tidak satu suara, ada yang mengatakan dari portugal sebab dalam kamus bahasa portugal terdapat kata tanger (senar atau dawai), pendapat lain mengatakan seniman ini dari Kekhalifahan Turki Usmani. Untum yang terakhir ini, kehadiran tanjidor diperuntukan sebagai hiburan Khalifah dan pejabat tinggi di istananya (para Pasya). Bukti arkeologisnya terdapat pada pertunjukan sejenis Tanjidor yang dimainkan oleh masyarakat di Mesir bernama Hasballah, yang termasuk satu wiayah kekuasan Turki Usmani.
Baik pemerintah kolonial maupun pemerintah Turki Usmani, barangkali juga Imperium lain, para seniman Tanjidor dalam hal ini, dihadirkan untuk memberikan hiburan dan semangat nasionalisme. Berbeda jauh manakala kita meninjau kehadiran seniman Tanjidor di Nusantara khususnya di pesisir laut Jawa.
Seniman tanjidor merepresantasikan diri sebagai seniman rakyat yang bebas-merdeka. Mereka memanfaatkan betul tanjidor sebagai kesenian rakyat yang dibedakan dengan sifat kesenian ala keraton (wayang-gamelan). Irama Tanjidor menghentak, membangkitkan semangat seperti ombak dan bisa dimainkan di mana saja baik dengan diam atau dengan berjalan. Lebih mencengangkan lagi, kesenian yang diperkenalkan bangsa Belanda (yang notebene “penjajah-Kristen”), menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan islam dan menjadi sarana pembinaan masyarakat Muslim. Sebagaimana bisa kita lihat dengan apa yang dicapai oleh seniman Tanjidor di desa Lembor-Brondong-Lamongan.
Dalam dimensi tertentu, Tanjidor baik yang di alunkan masyarakat Betawi di Jakarta maupun Warga Desa Lembor, Brondong, Lamongan atau desa-desa muslim lain, telah bertransformasi sebagai media dakwah yang mengingatkan kita dengan pilihan cara dan strategi dakwah para Walisongo. Yang berhasil menemukan-mengawinkan nyawa budaya dan inti terdalam ajaran agama islam. Ijtihad dakwah itu terbukti berhasil tanpa harus menimbulkan pertentangan serius atau bahkan mengalirkan banyak darah sebagaimana yang terjadi di wilayah timur tengah hingga dewasa ini.
Melalui kesenian dan kebudayaan sejenis, para wali membangun metode dakwah bercorak sufistik, menawarkan sudut pandang baru yang tidak hanya sebatas benar dan salah. Namun juga mengajari masyarakat menemukan makna hidup yang sebenarnya.
Buku Alur Alun Tanjidor Lembor-Brondong-Lamongan (1952-2019)
Saya pribadi merasa terkesan dengan cara penulis menyajikan data, merunut rangkaian peristiwa-peristiwa yang berlangsung sepanjang Tanjidor mengalun di Desa Lembor. Terutama metode dan cara pengungkapan hasil dengan bahasa yang cenderung bisa diterima semua kalangan. Hal lain yang tak kalah mengesankan adalah keberhasilan penulis memaparkan kenyataan yang berada di luar jangkauan asumsi-asumsi banyak orang terkait Tanjidor di Lamongan, terlebih di Desa Lembor.
Buku ini tidak tebal. Hanya 160 lembar. Tapi proses penulisannya melewati jalan yang terjal dan penuh kelok. Kurang lebih 10 bulan, sang penulis berjibaku di bawah terik matahari, menyusuri panas aspal sepanjang jalan raya Kalitengah, Brondong sampai Ujungpangkah, Gresik. Menemui para sepuh seniman yang tersisa untuk melakukan wawancara.
Benar saja, proses jarang sekali menghianati hasil. Buku ini lahir dengan cerita yang berwarna. Barang kali perlu saya katakan, tanpa buku ini, bisa saja kesenian tanjidor di Desa Lembor tidak lagi diketahui bagaimana dan dari mana asalnya. Buku ini cukup berhasil menjelaskannya.
Tentu saja kekurangan tetap ada, semisal hasil wawancara yang barangkali perlu ditulis dengan menggunakan bahasa masyarakat secara apa adanya, agar kesan lokalitas tersampaikan, dalam buku ini hal tersebut tidak tampak.
Meski demikian, kekurangan tersebut tidak mengurangi penghargaan bagi penulisnya.
Sebab pada kenyataannya, kajian tentang Kesenian-Budaya rakyat dengan peradaban Islam yang mengambil kajian desa sebagai obyeknya, (sebatas pengetahuan saya) sangat jarang dilakukan. Meskipun sudah banyak orang mengamini, melalui desa-desalah peradaban Islam tumbuh. Tentunya, fakta yang demikian itu sangatlah menarik apabila kajian-kajian tersebut berhasil disusun menjadi buku seperti buku ini.
Pada titik ini, saya melihat kesungguhan yang cukup besar penulisnya, sehingga buku ini bisa lahir. Sebab harus diakui, bahwa buku yang mengulas seputar desa masih sangat lemah. Ini disebabkan, bisa jadi karena urusan semen, pasir dan batu lebih penting dari catatan seputar desa menjadi buku. Dengan kata lain, mayoritas desa lebih butuh pengecoran daripada penulisan tentang masalalu dan asal usul sebuah desa.
Akhirnya, hadirnya buku ini diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung antara generasi muda (baca: Milenial) yang saat ini lebih menikmati dan menghayati kesenian asing kontemporer dari pada menikmati minimal menghayati (untuk tidak mengatakan lupa) produk dari cipta, rasa dan karsa seniman dan pelaku kebudayaan leluhurnya sendiri.
Dalam hal ini, barangkali perlu diajukan sebuah pertanyaan kepada kita semua: kapan terakhir kali kita mendengar alunan musik tradisional di desa kita masing-masing?
Judul buku : Alur Alun Tanjidor Lembor, Brondong, Lamongan (1952-2019)
Penulis : A.H J Khuzaini
Penerbit : Russa
Tahun Terbit Beserta Cetakannya : Cetakan kedua, November 2019
Tebal Buku: xx+160 Halaman
ISBN: 978-602-7095-92-2
Resensator : M Riyadhus Solihin